Sopir Mengerti Profesor Dihargai
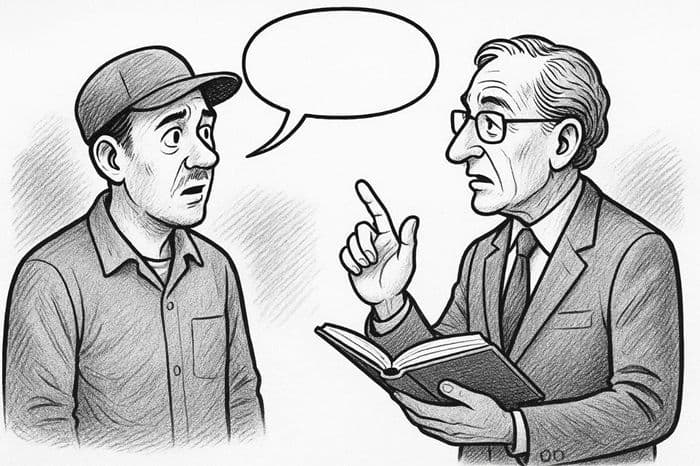
Ilustrasi. (Foto: istimewa/mistar)
Oleh: Bersihar Lubis
Anda pasti kerap bingung membaca singkatan dan akronim seperti DPPKAD, Kesbangpolinmas, dan Baperjakat. Konon, di Pangandaran, Jawa Barat, ada instansi bernama BP3APK2BPMPD, singkatan dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa. Wah, sangat panjang.
Lembaga BP3APK2BPMPD dibentuk pada tahun 2014. Pada akhir tahun 2016, lembaga ini dibagi menjadi dua dinas terpisah untuk memudahkan pembagian tugas. Yang satu bidang Pemberdayaan Perempuan, satunya lagi bidang Pemerintahan Desa.
Namun karena sudah merupakan lembaga atau badan yang resmi, kaum jurnalis pun menulisnya dalam berita. Bahasa birokrat telah merasuk ke dalam bahasa berita.
Bahasa berita sejatinya bersifat langsung dan mudah dimengerti. Tapi kadang ada jurnalis yang menuliskan surat edaran kementerian lengkap dengan nomor surat, tanggal, dan perihalnya. Padahal mestinya cukup dituliskan surat edaran kementerian tentang apa misalnya, tanpa harus menyebut nomor surat.
Baca Juga: Sebutlah Soeharto Apa Adanya
Bahasa birokrat ini teringat lagi ketika kita baru merayakan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Saya terkenang Susi Pudjiastuti, saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Meski secara usia tak lagi muda, ia memiliki gaya bahasa yang nyentrik, keluar dari stereotip umum bahasa birokrat.
Susi melarang penggunaan bahasa birokrasi yang ambigu. Ia ingin komunikasi dinas di lembaganya lebih transparan dan terukur. Misalnya, ia tidak mau digunakan kata peningkatan yang maknanya nggak jelas. Dia mau pilihan kata yang lebih pasti, misalnya: pembelian alat tangkap ikan.
Susi pernah berseloroh dalam rapat kerja dengan DPD RI di Gedung Nusantara II, ruang GBHN pada 2014 silam. "Mohon maaf kalau saya gaya bicaranya kayak begini. Kemarin saya cari kamus birokrat, tetapi enggak dapat," ujar dia. Sontak, sejumlah hadirin tertawa.
Di awal masa jabatannya, Susi membuat surat edaran melarang bawahannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan memakai “kata-kata bersayap” dalam menyusun program dan anggaran. Kata-kata bersayap, kata jebolan SMA kelas 2 ini, “bikin saya pusing.”
Kita memang kerap pusing oleh kata-kata dan gaya bahasa birokrat yang sering kali melenceng dari makna sebenarnya. “Harga bensin disesuaikan” kenyataannya dinaikkan. “Pencuri diamankan polisi” seakan-akan menjadi lebih enak, padahal ditangkap.
Ironis. Kegemaran memakai kata dan bahasa “tinggi” yang ujungnya tak bisa dimengerti. Seolah berbicara dan menulis secara ruwet akan menunjukkan kepintaran. Padahal semakin ruwet akan semakin kabur masalah yang dibicarakan.
Dalam birokrasi, kata-kata bersayap adalah eufemisme. Misalnya, “pendampingan nelayan.” Padahal yang terjadi adalah pengecatan perahu. Tentu saja sebuah proyek. Dan proyek adalah uang. Apa manfaat bagi nelayan? Jelas tak ada karena nelayan lebih memerlukan harga solar yang terjangkau, aturan yang simpel dan jelas, juga harga dan pasar tangkapan mereka yang terjamin.
Baca Juga: Inflasi di Sumut: Habis Cakak Takana Silek
Jangan-jangan birokrasi kita melempem pangkal masalahnya karena bahasa yang dipakai adalah bahasa formal yang gagah tapi tak efektif, yang seolah-olah berwibawa padahal kosong makna.
Kejelasan bahasa itu perlu dan utama sebelum kerja-kerja besar dalam pemerintahan dan pembangunan. Sebab realita tak terbentuk dari jargon.
Narasi birokrasi secara awam lekat dengan stempel “tak efektif”, “lambat”, “kaku”, bahkan “menyebalkan.”
Kata birokrasi berasal dari kata bureau (bahasa Prancis) yang kemudian diasimilasi oleh Jerman. Artinya adalah meja atau kadang diperluas jadi kantor.
Sebab itu, terminologi birokrasi adalah aturan yang dikendalikan lewat meja atau kantor. Di masa kontemporer, birokrasi adalah "mesin" yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di organisasi baik pemerintah maupun swasta.
Pada pucuk kekuasaan organisasi terdapat sekumpulan orang yang menjalankan kekuasaan. Dalam konteks negara, mereka misalnya parlemen atau lembaga kepresidenan. Mereka bekerja tidak sesuka hati, tetapi berdasarkan UU, peraturan pemerintah, dan berbagai regulasi lainnya.
Namun ada satu cerita yang lucu di sebuah daerah di era Orde Baru. Seorang kontraktor dari luar daerah mendatangi Kepala PU untuk meraih proyek. Tentu saja si Kepala PU risih karena proyek ditentukan berdasarkan tender atau lelang. “Silakan ikuti tendernya, Pak,” kata si Kepala PU.
Eh, spontan si kontraktor berang. “Kau tak tahu berhadapan dengan siapa. Aku ini ipar Bupati,” sergahnya. Tak ayal kejadian itu pun masuk koran. Wartawan pun menulis, “Ipar Bupati Memaksa Minta Proyek.”
He-he, mana ada Bupati punya ipar. Bupati itu jabatan di pemerintahan, yang kala itu dipilih oleh DPRD. Bukan kerajaan yang terpilih karena faktor genealogis alias turunan.
Bahasa mencerminkan bangsa, konon begitu kata peribahasa. Jika Indonesia masih ada yang kusut, barangkali karena pemakaian bahasanya masih perlu dibenahi agar lebih rasional, efisien, dan beretika demi kepentingan rakyat.
Baca Juga: Menjelang Revalidasi UNESCO, Penggiat Nilai Istilah ‘Orang Tertular Geopark’ Hanya Jargon Kosong
Bahasa Jargon
“The trick is to talk to be understood by the truck driver while not insulting the professor’s intelligence.” (Caranya adalah berbicara agar dimengerti sopir truk tanpa merendahkan kecerdasan sang profesor) — Ed Murrow. (Chapman & Kinsey, 2009:35)
Begitulah, bahasa berita. Sederhana saja. Mudah dimengerti oleh pembaca. Jangan sampai pembaca bingung, apalagi stres.
Pakailah kata-kata atau istilah yang pengertiannya diketahui rata-rata orang. Tanpa perlu mengerutkan jidat, pembaca langsung paham. Jika terpaksa memakai istilah asing, bikinlah padanannya dalam bahasa Indonesia.
Sebaiknya, jangan tergoda menggunakan istilah-istilah teknis yang hanya dimengerti kalangan tertentu.
Covid-19 adalah istilah teknis di Kementerian Kesehatan. Padanan katanya adalah penyakit wabah corona. Jangan sampai masyarakat yang memperoleh bantuan sembako atau bantuan sosial tunai berpendapat, jika wabah corona terus merajalela maka bantuan sosial terus mengalir.
Kerap sekali wartawan menuliskan jargon dalam berita. Yakni, istilah teknis atau ungkapan khas yang hanya digunakan di kalangan tertentu, seperti hakim, dokter, dan polisi. Padahal maknanya hanya dipahami pelaku profesi secara persis. Contohnya, daftar pencarian orang (DPO) adalah jargon di kepolisian. Makna spesifiknya hanya dipahami kalangan polisi.
Pembaca bisa menafsirkannya secara beragam. Mencari siapa, kok pakai daftar, dan mengapa dicari, begitu mungkin orang awam menebak-nebaknya. Padahal maksudnya adalah orang-orang yang diburu polisi atau “wanted” yang dulu dikenal dalam film koboi.
Saya merasa penggunaan jargon dalam berita perlu dikurangi atau tidak sama sekali. Jika terpaksa juga, berilah penjelasan di dalam tanda kurung.
Masih ada akronim atau singkatan seperti Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), karhutla (kebakaran hutan dan lahan), RDP (rapat dengar pendapat), DIM (daftar inventarisasi masalah), dan lainnya.
Baca Juga: Macbeth yang Mabuk Kekuasaan
Ada pula kegemaran menaburkan bahasa asing dalam berita. Memang, umumnya berasal dari para narasumber. Tak jelas apakah karena sudah menjadi kebiasaan atau hanya sekadar supaya terkesan keren.
Tak hanya para pejabat, juga kaum selebritas, politikus, ekonom, pelaku ekonomi, dan artis gemar berbahasa asing terutama bahasa Inggris. Misalnya, menggunakan istilah memorandum of understanding ketimbang “nota kesepahaman.”
Dalam berita juga demikian. Misalnya, PSMS leading dari Semen Padang dengan dua gol. Padahal leading bisa diganti dengan kata unggul.
Event Festival Danau Toba dibatalkan tahun ini. Mengapa event tak diganti dengan kata kegiatan. Atau malah tak dipakai sama sekali karena festival adalah event juga!
Bahkan, kita sering membaca kata owner (pemilik), launching (peluncuran), special report (laporan khusus), dan reshuffle (perombakan).
Malahan juga lebih memilih kata reformasi ketimbang perubahan, relaksasi daripada pelonggaran, “sosialisasi” ketimbang “pemasyarakatan”, dan “akselerasi” ketimbang “percepatan.”
Repotnya, terhadap nama institusi, badan usaha, atau korporat seperti Merdeka Walk, Deli Park, Kualanamu International Airport (KNIA), dan Ojek Online, tak bisa diutak-atik. Wartawan tak bisa bilang “pisang.” Sudah telanjur keinggris-inggrisan.
Bahasa asing itu juga muncul dalam narasi berita. Bukan hanya dalam kutipan langsung dari para narasumber. Padahal wartawan bebas untuk tak menggunakan istilah asing dari narasumber jika menjadikannya kutipan tidak langsung.
Berita itu sederhana. Orang awam seperti buruh, petani, nelayan, dan pedagang kaki lima pun merasa bahasa berita tidak terlalu tinggi. Tapi intelektual dan birokrat merasa bahasa yang dipakai tidak terlalu rendah. Sederhanakan saja, jangan diperumit. **
** Penulis adalah jurnalis menetap di Medan























